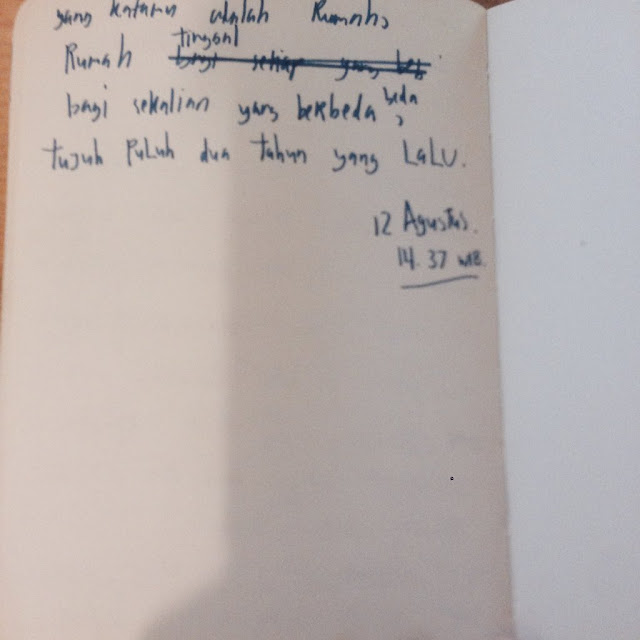Pernahkah kita memikirkan rumah dan
perasaan-perasaannya dan berpikir bahwa rumah juga merindukan kita? bahwa ternyata ketika kita
pergi jauh, rumah tetap sama, ia tidak bergerak, ia masih pada tempatnya dan ia
menyimpan semua kenangan kita.
Selama 34 tahun hidup saya, saya menghitung (semoga
tidak ada yang terlewat di dalam ingatan saya) saya telah menempati sekitar 15
rumah tinggal dan itu sudah termasuk
rumah kos saya ketika berada di perantauan. Rumah pertama adalah sebuah rumah
besar di kota Larat, saya mengingat sebuah rumah tua dengan
kamar-kamar luas dan jendela model lama dengan cat kayu berwarna hijau
tua. Saya mengingat rumah ini dengan anjing kampung bernama Boy, yang selalu
menanti ayah saya ketika pulang dengan perahu motornya dari pulau-pulau seberang. Juga aroma menyengat bunga terompet yang sering masuk ke kamar tidur. Ketika tinggal di rumah ini, usia
saya barangkali satu atau dua tahun, sehingga saya merasa rumah itu besar
sekali.
Rumah ke dua (yang bagi saya istimewa) adalah rumah
tua milik keluarga kami, milik kakek saya, Marthen Elwarin yang menikah dengan
Dorkas Elwarin. Dorkas Elwarin, seorang perempuan Jawa yang bernama asli
Sutijem jatuh cinta dengan kakek saya ketika ia bertugas di Semarang.
Mereka kemudian menikah dan pulang ke Ambon. Dorkas Elwarin yang kemudian kami
panggil “Oma Jawa” lalu menjadi seorang Kristen yang taat. Mereka menempati sebuah rumah mungil di daerah Kudamati. Rumah yang
kemudian melahirkan banyak anak cucu di sana. Rumah kecil dan sederhana yang
biasanya menampung anak cucu dari segala penjuru untuk tinggal di dalamnya. Mengingat keluarga kami lumayan besar.
Saya tumbuh dan besar di rumah ini. Kedua orang tua
saya melanjutkan pekerjaan mereka sebagai pendeta di pulau. Sementara saya dan
kedua kakak perempuan saya dititipkan di rumah ini. Saya yang masih kecil
dititipkan berpindah tempat, rumah lainnya adalah milik Tante (adik perempuan ayah) di daerah Batu Gantung.
Tapi dapat dibilang saya lebih banyak menghabiskan waktu tinggal di Kudamati—Kampong
Tai, sebutan bekennya pada saat itu, sebelum akhirnya menjadi lebih kini dengan
sebutan ‘pelor’ atau singkatan dari: penghuni lorong.
Bermain di lapangan Oma Dana. Berlari di sepanjang
jalan-jalan setapak bersama sahabat kecil saya, Donny Toisuta, biasanya disapa Odon. Memanjat pohon
kersen milik keluarga Odon, dan biasanya suka ditegur oleh Oom Anton (ayah Odon) atau Oma Nes (neneknya).
Atau bermain masak-masakan bersama sahabat kecil saya lainnya, Theophanny
Rampisela, biasanya disapa Kaka, hanya dengan memakai kaus kutang dan celana
dalam. Atau bermain beramai-ramai: enggo sambunyi, afiren, sandiwara
pedang-pedangan tutur tinular, gambar, pata-pata, lompat karet, gici-gici, dan permainan
semasa kecil lainnya di tahun 90-an pada waktu itu membuat saya merasa sangat beruntung.
rumah tua kami yang bercat hijau di sebelah kiri bersama dengan setapak-setapak itu.
Ingatan lainnya yang tidak hilang adalah ketika malam jelang Paskah kami akan berkumpul di lapangan Oma Dana untuk menonton layar tancap
film Yesus disalib. Atau tidak tidur semalaman karena
menunggu pawai obor subuh-subuh. Selain itu saya juga tidak pernah lupa latihan menyanyi atau baca puisi di teras rumah. Memasuki masa remaja saya juga membagi tempat
tinggal saya, dengan rumah di belakang Rumah Sakit Tentara, kemudian rumah di
Kebun Cengkeh. Tapi tetap saya kembali ke rumah di Kudamati—Kampong Tai.
Kebiasaan bertelanjang kaki dan berjalan
di sepanjang setapak, hingga kebiasaan memikul handuk (dan kemudian berakhir
dengan tidak mandi juga) masih membekas dengan jelas di kepala saya—semua seperti
baru kemarin. Padahal hal ini terjadi puluhan tahun yang lalu. Hingga saat ini,
bahkan ketika saya sudah merantau dan tinggal sendiri, ingatan-ingatan ke
masa-masa itu seringkali muncul di dalam kepala saya, biasanya ia datang
berupa: bebunyian daun pohon Mangga yang ada di depan rumah, bunyi seng yang
berderit ketika ditiup angin, lolongan anjing ketika malam,
atau aroma panggangan kue dari tetangga sebelah.
Ingatan-ingatan membawa saya ke setapak-setapak itu kembali, saya menjadi anak kecil
yang sama, masih suka berlari dengan ringan—atau bermain sepeda di dalam becek
di lapangan Oma Dana. Menghitung rumah-rumah yang saya lewati ketika keluar
dari rumah tua kami menuju ke depan lorong Andre, tempat menunggu angkutan umum: rumah ibu batak, rumah (bekas) Oma
aya, rumah (bekas) keluarga Manusiwa, rumah tante Masbait, rumah Oom Nus
Tarantein, rumah Oom Cak Lesilolo, rumah keluarga besar Lesilolo, rumah
keluarga besar Tumallang kiri dan kanan, rumah Mama Kety, rumah keluarga
Kriekhoff, rumah Om No Louis.
Rumah-rumah yang saya sebutkan ini barangkali sudah tidak
ditempati oleh penghuni aslinya lagi. Namun kenangan tentang setapak yang menjaga kaki-kaki
telanjang saya berlari di masa kanak-kanak, tak pernah hilang—kenangan itu
begitu girang dan bersahabat di dalam kepala, tinggal bersama rumah-rumah yang
tetap berdiri di sepanjang jalan setapak itu: walau penghuni dari rumah-rumah
itu barangkali sudah tak lagi tinggal di situ karena meninggal atau pindah
kota. Jika sudah begini, rindukah kamu kepada rumah yang dulu pernah kamu
tinggali lama?
***
(selesai menulis ini saya jadi kepikiran untuk
memotret rumah-rumah yang pernah saya tinggali—di kota Ambon maupun di
kota-kota lainnya jika memungkinkan dan membuat sebuah cerita pendek tentangnya. atau mungkin membuat pameran serial rumah yang lain.)